Dalam perjuangan kita melawan kekerasan seksual di negara ini. tak lain dan tak bukan adalah dengan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Tidak ada yang lain.
Saya seharusnya berusaha melanjutkan serial “Unbelievable” di Netflix. Tetapi baru sampai di episode 4, hati dan jari saya sudah tidak bisa diajak kompromi. Saya harus menuangkan perasaan saya tentang apa yang saya tonton di serial ini. Jadi karena toh saya sudah ditinggal oleh teman Netflix Party saya sejak dari episode pertama, karena dia merasa serial ini sangat triggering, maka kenapa tidak saya berhenti sejenak dan menulis artikel tentangnya.

Artikel ini bukan review menyeluruh tentang dari “Unbelievable”, namun lebih kepada bagaimana perasaan saya saat menonton episode demi episodenya. Bagi saya, serial Unbelievable merobek semua stereotip kita (paling tidak stereotip saya pribadi) tentang kejadian perkosaan dan bagaimana korban meresponnya.
1) Korban perkosaan bisa sangat beragam
Saya yakin banyak dari kita yang berpikir bahwa perkosaan hanya bisa terjadi pada perempuan-perempuan cantik berpakaian seksi yang keluar malam-malam sendirian. Serial ini memaparkan kejadian yang mungkin sulit diterima akal sempit kita. Bahwa perkosaan bisa terjadi pada seorang anak baik-baik yang menjalani kehidupan sehari-harinya tanpa neko-neko, bekerja di department store pulang pergi naik sepeda dengan baju tertutup. Seseorang menyelinap masuk kamarnya dan memerkosanya saat subuh saat ia sedang tidur pulas. Perkosaan bisa terjadi pada seseorang secara fisik tidak dianggap menarik oleh masyarakat, pada seorang wanita obesitas berambut keriting yang berpakaian lusuh. Bahkan perkosaan dapat terjadi pada perempuan lanjut usia.
2) Bahwa di negara maju dengan sistem hukum yang sudah terstruktur rapi saja masih sulit bagi korban untuk mencari keadilan, bagaimana dengan di negara kita?
Dalam film ini digambarkan bagaimana korban sudah sangat tanggap, segera menelpon polisi sesaat setelah kejadian, polisi segera mengantar korban ke RS untuk visum. Di RS, dokter sudah memiliki instrumen, yang mereka sebut rape kit, untuk memeriksa korban secara detail. Pasien diambil sampel-sampel sel tubuhnya, diambil darahnya, difoto seluruh tubuhnya, diperiksa area panggulnya (pelvic exam), diberikan morning after pil untuk mencegah kehamilan dan antibiotik untuk profilaksis.
Jujur saja, 10 tahun lebih saya berprofesi sebagai dokter dan menangani beberapa kasus perkosaan, tidak pernah saya melakukan pemeriksaan selengkap itu, selain karena saya tidak pernah diajari bagaimana protap menangani pasien korban perkosaan juga karena di tempat saya bekerja saat itu tidak ada instrumennya.
3) Bahwa tidak semua korban bereaksi seperti yang kita kira.
Entah apa yang merasuki otak kita selama ini tapi saya yakin banyak dari kita yang berpikiran bahwa korban perkosaan selalu bereaksi histeris atau justru kaku tidak bisa berbuat apa-apa, yang tentu saja respon seperti itu sangat bisa saja terjadi. Tapi serial ini menunjukkan bahwa bukan itu satu-satunya reaksi yang valid.
Dalam serial ini, bahkan tidak ada satupun korban yang menangis. Salah satu korban bahkan menjawab semua pertanyaan polisi dengan tersenyum! Dengan tersenyum! Mungkin kita akan bertanya-tanya dan mulai menghakimi dalam hati, apa benar dia diperkosa? Kok bisa masih senyum-senyum usai diperkosa? Nyatanya, bisa. Mengapa tidak? Setiap orang berespon berbeda pada setiap kejadian, bukan berarti apa yang terjadi pada mereka tidak valid.
4) Bahwa memang lebih sulit bagi laki-laki untuk bisa berempati dengan korban perkosaan perempuan.
Dalam serial ini dan saya rasakan sendiri di dunia nyata, figur otoritas laki-laki memang sulit merasa relate dengan kejadian perkosaan pada perempuan, akibatnya tidak ada manifestasi empati dalam tindakan. Tidak ada usaha lebih atau keinginan pantang menyerah mencari keadilan bagi korban. Kenapa begitu? Karena memang laki-laki tidak memiliki pengalaman ketubuhan yang sama dengan perempuan. Bukan berarti menggeneralisir bahwa perempuan bisa otomatis empatik pada perempuan korban perkosaan, (karena banyak juga perempuan yang empatinya nihil terhadap perempuan korban) tetapi dalam serial ini tergambar nyata bagaimana Grace Rasmussen dan Karen Duval sebagai tokoh utama detektif memberikan 110% diri mereka dalam upaya mencari pelaku dan mencegah korban berikutnya.
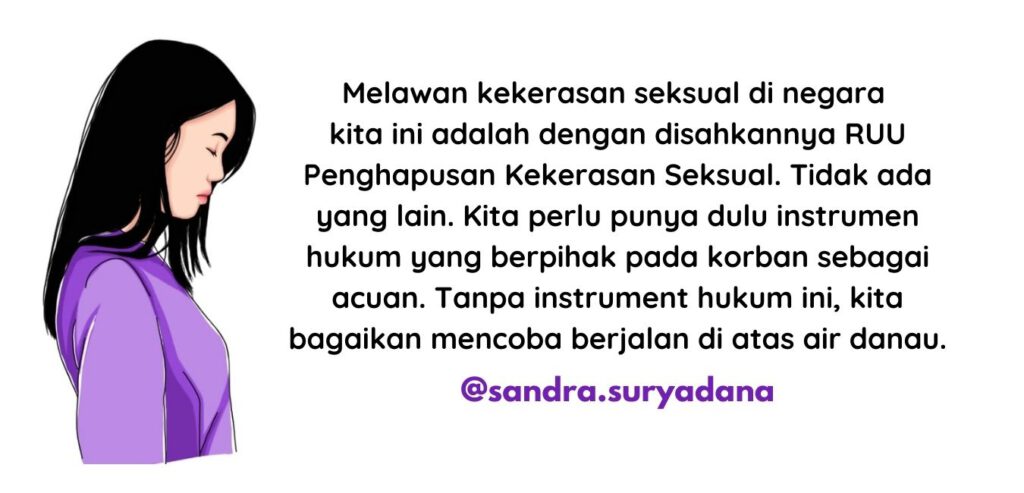
Di tengah kesibukan mereka, mereka masih harus mendorong rekan kerja laki-laki mereka untuk lebih peduli pada kasus perkosaan ini. Saya sudah sampai pada adegan di episode 4 di mana Grace Rasmussen walk out dari ruang meeting dengan pimpinan FBI yang adalah laki-laki, karena beliau seakan menutup mata pada data statistik yang terpampang nyata bahwa rata-rata anggota polisi 2-4x lebih sering melakukan kekerasan pada anggota keluarganya dibanding masyarakat awam dan bahwa seseorang yang pernah melakukan kekerasan pada perempuan memiliki kemungkinan sangat besar untuk melakukan kekerasan seksual di masa mendatang. Grace hanya bisa berteriak “Where is the outrage?!” menghadapi rekan kerja laki-laki yang menganggap semua statistic tersebut hanyalah angka-angka beterbangan.
5) Bahwa bagaimana instrument hukum yang tepat sasaran dan penegak-penegak hukum yang berhati nurani adalah ujung tombak dari perjuangan kita melawan kekerasan seksual.
Di episode 4, Grace Rasmunsen dengan tegas menyampaikan bahwa poster-poster himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati sama sekali tidak bermanfaat, justru hanya menjadi bahan olok-olok bagi pelaku. Adalah tugas dari penegak hukum untuk memastikan masyarakat tetap hidup aman meskipun mereka lupa menutup jendela atau mengunci pintu.
Adegan ini membuat saya memikirkan ulang peribahasa yang sering muncul di benak saya setiap menonton film kriminal “Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga.” Yah mungkin benar, tapi bila tidak ada yang menangkap tupai yang jatuh itu, maka tentunya si tupai akan segera melompat lagi kesana kemari seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sama halnya, bila negara gagal menyediakan instrument hukum yang ampuh dan penegak hukum tidak mampu bertindak tegas berdasarkan hati nurani dan hukum yang berlaku, maka “tupai-tupai” itu akan terus berlompatan dan korban-korban akan terus berjatuhan.
Tidak ada yang lain, negara ini butuh UU P-KS
Sekarang hati dan otak saya sedang beradu argumen. Hati saya ingin segera menuntaskan serial ini untuk mengetahui akhir kisah dari Marie Adler, Amber dan Mama D, apakah mereka berhasil mendapatkan keadilan. Tetapi otak saya sudah 2 hari teraduk-aduk serial ini dan sudah menganalisa bahwa seharusnya tubuh dan mata saya diistirahatkan.
Tapi bahkan dengan mata terpejam saya tetap memikirkan bagaimana jadinya di negara kita? Di mana negara ketika rakyat butuh? Di mana penegak hukum ketika rakyat mencari? Di mana kita ketika ada kekerasan seksual di sekitar kita?
Akhirnya saya sampai pada simpulan, bahwa titik terang pertama dalam perjuangan kita melawan kekerasan seksual di negara kita ini adalah dengan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Tidak ada yang lain. Kita perlu punya dulu instrumen hukum yang berpihak pada korban sebagai acuan. Tanpa instrument hukum ini, kita bagaikan mencoba berjalan di atas air danau.
Basah dan tidak tahu kapan kita akan tenggelam. RUU ini adalah pasak-pasak kayu yang bisa kita injak untuk melangkah dan penegak-penegak hukum dan instrumen layanan masyarakat adalah kayu-kayu melintang yang merangkai menjadi jembatan yang makin memudahkan kita menuju pulau pengharapan.
Semoga saya bisa tidur nyenyak. Semoga kita bisa tidur nyenyak. Semoga para penentu kebijakan bisa tidur nyenyak. Semoga para penegak hukum bisa tidur nyenyak. Tapi saya yakin yang tidak akan bisa tidur nyenyak adalah para korban kekerasan seksual.
TENTANG PENULIS





